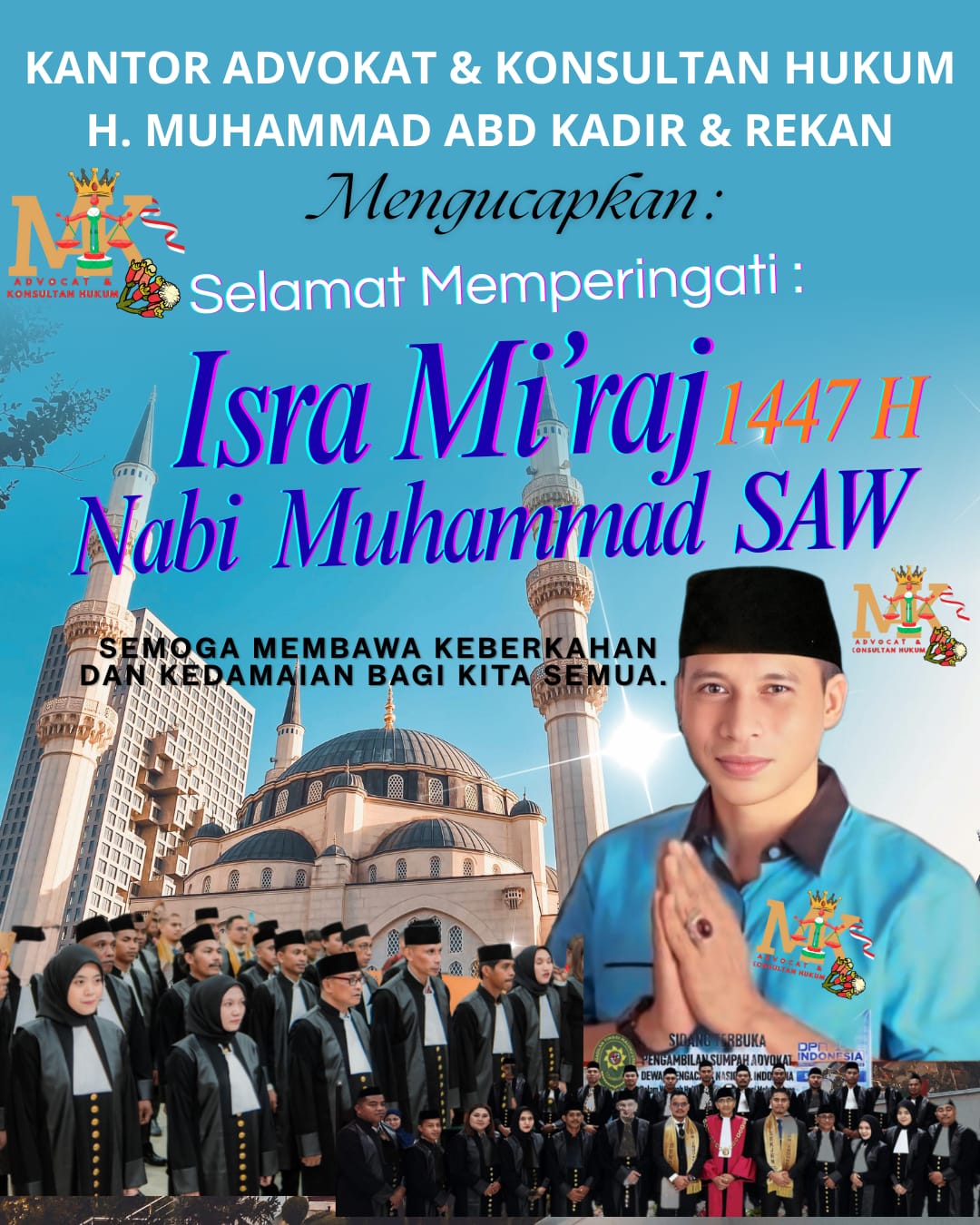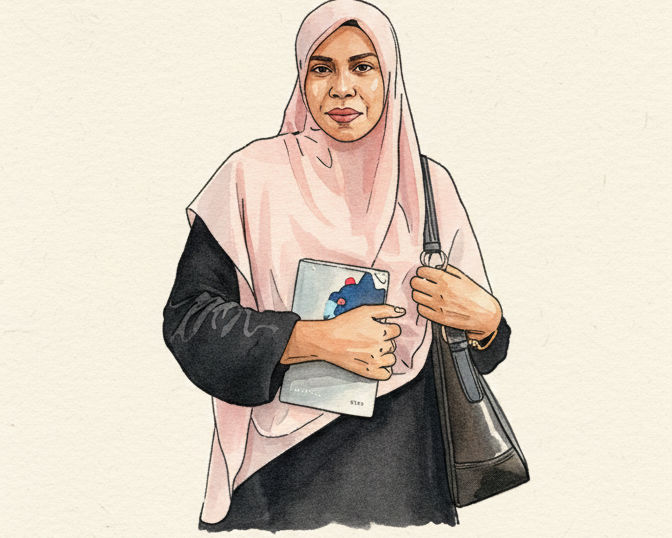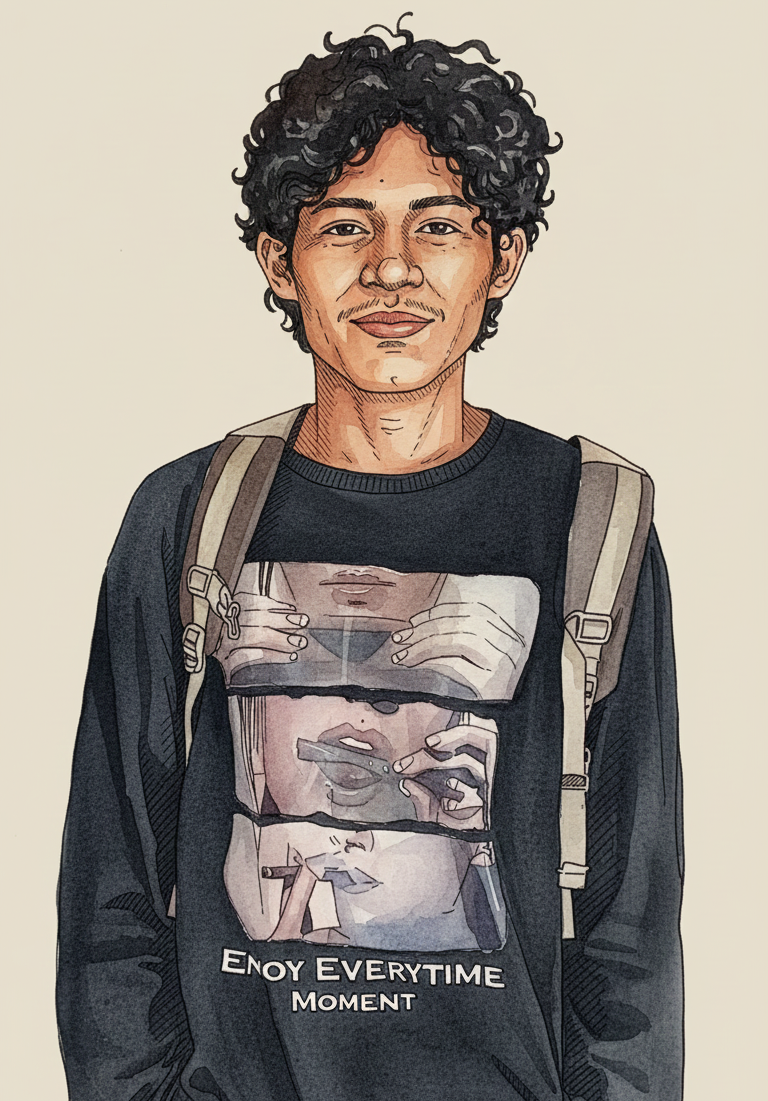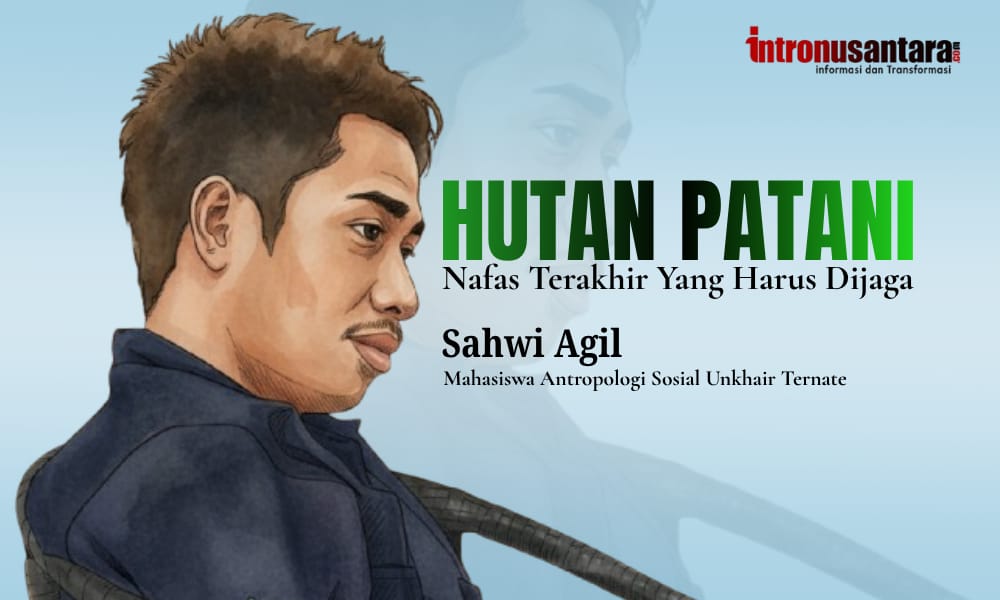Oleh : Nazar Umasugi | Kaders Forum Study Anak Sastra Maluku Utara (FORSAS-MU)
Membaca ekopopulisme dalam ranah problematika tambang di Maluku Utara menemukan momentumnya ketika masyarakat lokal harus berhadapan dengan gelombang besar industrialisasi ekstraktif yang menjanjikan pembangunan, tetapi meninggalkan luka ekologis yang dalam.
Ekopopulisme di sini tidak sekadar sebuah strategi politik, melainkan bahasa moral yang mengangkat rakyat sebagai subjek utama yang melawan dominasi negara dan korporasi. Dalam lanskap Halmahera dan Obi, narasi rakyat menghadirkan dirinya sebagai penjaga hutan, sungai, dan laut, sementara elite tambang berwajah ganda sebagai pembawa janji kemajuan sekaligus pembuka jalan menuju krisis ekologis.
Retorika ini memperlihatkan kontras tajam: antara air yang keruh dengan brosur hilirisasi hijau, antara suara nelayan yang kehilangan tangkapan dengan pidato pejabat yang mengagungkan transisi energi.
Ekopopulisme lahir dari moral ekonomi rakyat, sebagaimana Martinez-Alier (2002) jelaskan dalam The Environmentalism of the Poor, yakni kesadaran bahwa alam bukan hanya sumber daya, melainkan nadi kehidupan yang tak ternilai. Di Maluku Utara, klaim ini menemukan panggungnya.
Sungai yang berubah warna, tanah yang retak, dan laut yang tercemar menjadi simbol perjuangan yang mempersatukan komunitas. Escobar (2011) dalam Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World mengingatkan bahwa pembangunan yang berlandaskan pada kalkulus teknokratis cenderung meniadakan pengetahuan lokal, sedangkan Scott (1998) dalam Seeing Like a State menyoroti bagaimana proyek raksasa negara selalu berupaya menyederhanakan kerumitan hidup masyarakat demi memudahkan kendali, sering kali dengan konsekuensi kehancuran.
Dalam konteks ini, ekopopulisme menjadi jawaban politik tanding—sebuah cara berbicara dari rakyat yang menolak direduksi menjadi angka dalam laporan CSR atau tabel teknis AMDAL.
Di Halmahera, ketika industrialisasi nikel mengubah desa-desa pesisir menjadi tapak tambang dan kawasan industri, warga menegaskan dirinya sebagai pihak yang paling menderita sekaligus yang paling berhak menentukan arah pembangunan.
Suara mereka menggugat ketidakadilan distribusi manfaat dan beban, mengungkap paradoks di mana keuntungan tambang mengalir ke pusat kekuasaan, sementara risiko penyakit, rusaknya lahan, dan hilangnya mata pencaharian terjebak di tubuh rakyat kecil.
Di Pulau Obi, perlawanan serupa berlangsung, ketika kehidupan nelayan yang sederhana harus dipertukarkan dengan janji modernitas yang sering kali hanya menghasilkan upah rendah dan ketidakpastian. Tsing (2005) dalam Friction: An Ethnography of Global Connection, menyebut fenomena semacam ini sebagai friksi—benturan antara globalisasi modal dan keberhidupan lokal—yang justru melahirkan ruang bagi narasi tanding seperti ekopopulisme untuk hidup.
Namun ekopopulisme tidak hanya menyoal perlawanan, melainkan juga mengandung risiko. Ia bisa jatuh dalam kooptasi, ketika elite lokal mengklaim berbicara atas nama rakyat, tetapi justru mengubah perlawanan menjadi sarana patronase. Ia juga dapat menyempit menjadi retorika anti-proyek semata, tanpa membangun jalan keluar yang berkelanjutan.
Karena itu, sebagaimana diperingatkan oleh Li (2007) dalam The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, tantangan terletak pada bagaimana membingkai ekopopulisme bukan hanya sebagai negasi terhadap tambang, tetapi juga sebagai gagasan positif tentang tata kelola yang adil.
Dengan mengakui metis—pengetahuan rakyat tentang musim ikan, mata air, dan ritme tanah—ekopopulisme dapat menjadi jalan menuju pembangunan alternatif yang berpihak pada kehidupan.
Keberhasilan ekopopulisme dapat dilihat pada kasus masyarakat adat Kasepuhan di Jawa Barat yang berhasil mempertahankan hak kelola hutan melalui program Hutan Desa. Gerakan kolektif berbasis nilai lokal dan dukungan jaringan LSM memungkinkan masyarakat memulihkan lahan kritis sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui agroforestri yang lestari (Hakim, 2019).
Di Kalimantan Tengah, komunitas Dayak di Desa Tumbang Malahoi juga mampu menghalau ekspansi perkebunan sawit dengan memperkuat kelembagaan adat dan memanfaatkan kerangka hukum pengakuan hutan adat. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa ekopopulisme, ketika ditopang strategi politik dan hukum yang tepat, dapat menghasilkan tata kelola sumber daya yang memadukan keadilan sosial dan kelestarian ekologi.
Namun keberhasilan tersebut tidak datang tanpa hambatan. Di banyak tempat, gerakan ekopopulisme harus menghadapi kooptasi oleh elite lokal yang mengalihkan agenda perjuangan menjadi alat tawar-menawar politik. Hambatan lain muncul dari kriminalisasi aktivis dan minimnya dukungan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Di Maluku Utara, misalnya, perlawanan warga kerap dibungkam melalui stigma penghambat investasi, sementara ruang dialog formal masih didominasi bahasa teknokratis yang sulit diakses rakyat. Hal ini menggarisbawahi perlunya strategi penguatan kapasitas komunitas, literasi hukum, dan aliansi lintas sektor agar ekopopulisme tidak berhenti pada wacana moral, tetapi menjelma menjadi gerakan dengan daya tawar institusional yang nyata.
Dalam arus besar transisi energi global, Maluku Utara ditempatkan di pusat peta geopolitik nikel. Namun, tanpa keadilan sosial dan ekologis, transisi ini hanya akan menjadi bentuk baru dari green extractivism yang dilapisi retorika hijau.
Ekopopulisme berperan mengingatkan bahwa di balik slogan keberlanjutan terdapat wajah-wajah nelayan yang kehilangan ikan, petani yang kehilangan tanah, dan anak-anak yang kehilangan air bersih. Di sinilah letak kekuatan retoriknya: ia bukan sekadar wacana, melainkan jeritan moral yang menuntut diakuinya rakyat bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai pemilik sah masa depan.
Ekopopulisme di Maluku Utara tampil sebagai cermin dari perlawanan rakyat terhadap arus pembangunan yang timpang. Ia mengajak kita merenungkan kembali pertanyaan paling mendasar: pembangunan untuk siapa, dan dengan biaya apa? Ketika suara rakyat bersatu dengan bahasa moral ekologi, maka tambang tidak lagi hanya soal bijih nikel atau smelter megah, tetapi juga tentang hak hidup yang adil, tentang tanah dan laut yang diwariskan, serta tentang martabat yang tak bisa ditebus oleh angka investasi.
Inilah diskursus yang terus bergema, menantang negara dan korporasi untuk tidak lagi melihat rakyat sebagai objek, melainkan sebagai penentu arah sejarah mereka sendiri. (*)
**) Ikuti berita terbaru intronusantara di WhatsApp klik link ini dan jangan lupa di follow.