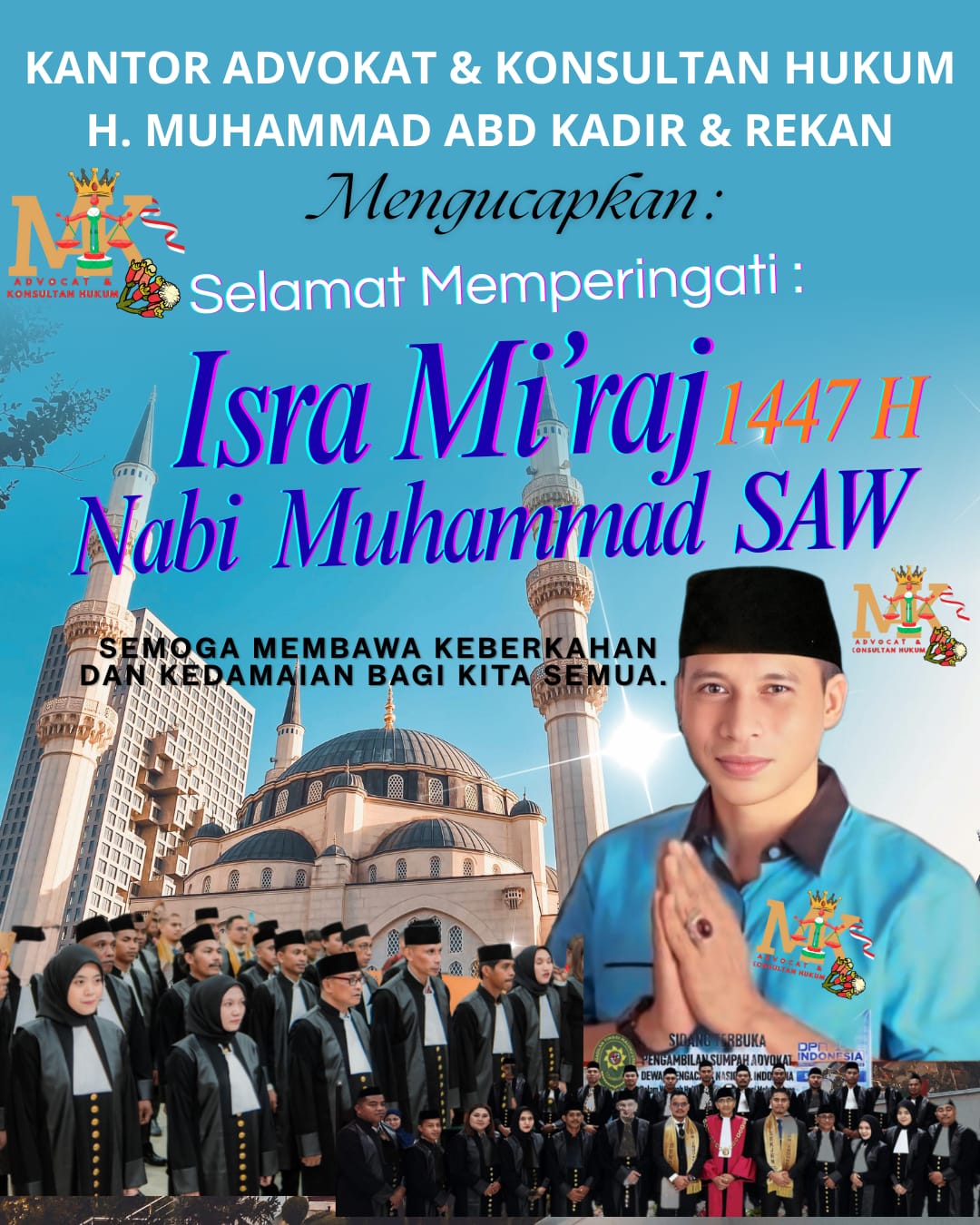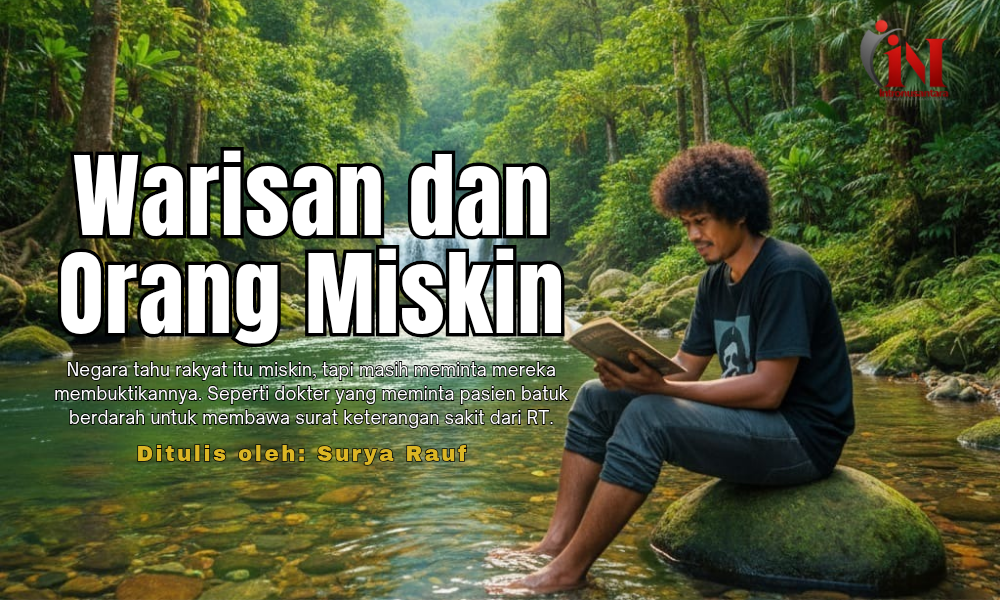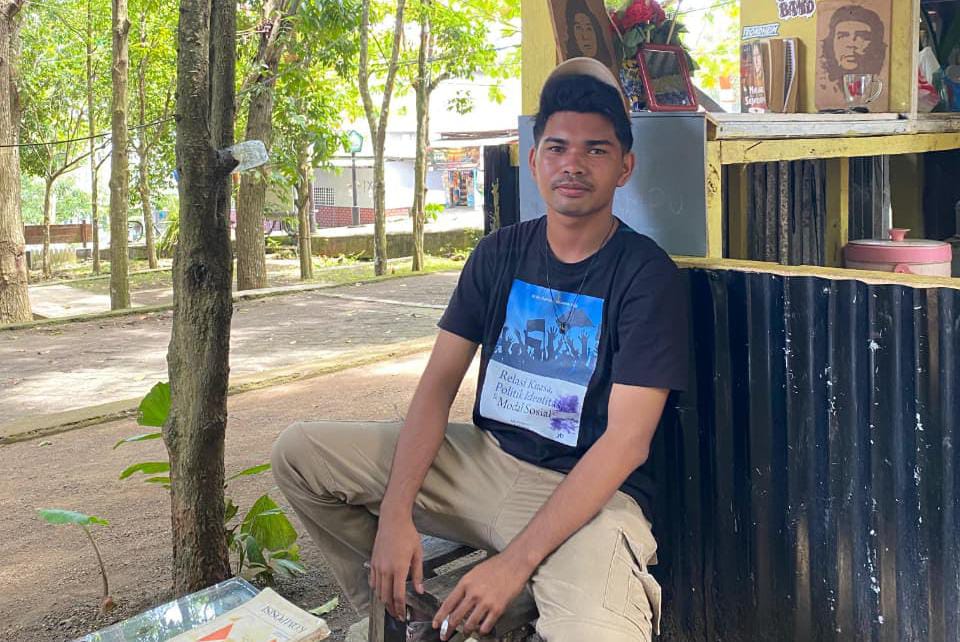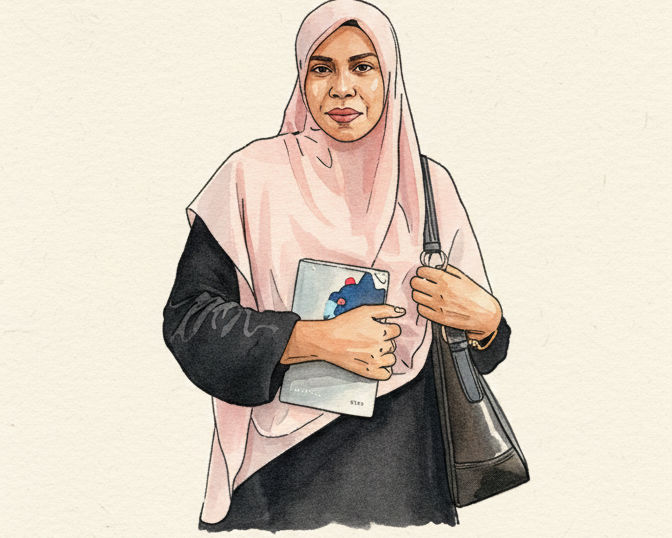Oleh: Surya Rauf
Ada seorang bapak di kampung. Warisan tanahnya luas, letaknya di nol kilometer jalan utama menuju Gedung BUPATI dan Bundaran Kota. Kalau pakai istilah makelar properti: “premium location”. Tapi jangan salah sangka, hidupnya bukan premium, bahkan tak jarang berhutang di warung tetangga. Setiap tahun datang sepucuk surat, bukan dari malaikat Izrail, melainkan dari malaikat pajak: SPPT PBB. Angkanya selalu naik, seperti doa-doa yang tidak pernah terkabul.
Beginilah nasib orang kecil di negeri besar: punya tanah, tapi miskin. Pemerintah melihat tanahnya dengan kacamata appraisal, seolah-olah setiap jengkal tanah itu bisa disulap jadi milik pribadi. Padahal ia hanya ladang singkong dan rumah berdinding papan.
Logika pajak kita sederhana: siapa punya tanah mahal, harus kaya. Kalau ternyata miskin, ya itu salah dia sendiri. Mengapa miskin tapi punya tanah mahal? Seakan-akan kemiskinan adalah kejahatan yang pantas dihukum dengan surat tagihan pajak. ( baca : Eko Prasetyo )
Pajak bumi dan bangunan selalu dielu-elukan sebagai “alat keadilan sosial”. Retorika para pejabat manis sekali: “rakyat berkontribusi demi pembangunan”. Namun, ketika tiba di meja rakyat, yang tersaji adalah piring kosong. Jalan rusak, sekolah bobrok, layanan kesehatan loyo. Yang kaya membayar konsultan pajak, yang miskin membayar dengan keringat. Bedanya, keringat tidak bisa dikreditkan dalam laporan fiskal.
Saya jadi ingat satu cerpen. Tokoh utamanya sering kere, tapi tetap bisa melucu di tengah nasib apes. Nah, rakyat kecil kita pun begitu. Ketika pajak naik ratusan persen di Jombang atau Pati, mereka bukannya menulis esai di media, melainkan membawa segalon uang koin ke kantor pajak sebagai bentuk protes. Sarkasme kelas rakyat: lebih ampuh daripada seminar akademik.
Sementara itu, para pejabat tersenyum di televisi, mengatakan semua “sesuai aturan”. Saya jadi curiga, aturan ini ditulis dengan tinta emas di atas kertas rakyat jelata.
Seorang kolumnis terkenal pernah menulis dengan lirih tentang jarak antara rakyat dan negara. Dalam pajak, jarak itu seperti jurang. Negara berdiri di tepi satu, memegang kalkulator, sementara rakyat di seberang, memegang panci kosong. Jurang itu diisi dengan jargon, peraturan, dan angka NJOP. Angka yang naik bukan seperti doa yang membebaskan, melainkan seperti kutukan.
Bayangkan sebuah rumah kayu tua yang berdiri gagah di samping jalan menuju Pandopo baru. Nilainya di mata appraisal mungkin miliaran. Tapi penghuninya masih menyalakan lampu teplok ketika listrik padam. Apakah keadilan berarti memaksa ia membayar pajak setara pengusaha properti? Ataukah keadilan itu menutup mata pada kenyataan, demi target Pendapatan Asli Daerah?
Seorang budayawan kondang berkata: pajak kita ini seperti cinta yang tidak adil. Kekasih meminta cincin berlian, padahal yang kau punya hanya kalung besi. Kalau kau tak mampu memberinya, kau dianggap tidak setia. Padahal kesetiaan bukan diukur dari harga cincin, sebagaimana nasionalisme tidak diukur dari angka PBB.
Lalu para ekonom akan berdebat: pajak adalah tulang punggung negara. Tanpa pajak, negara lumpuh. Betul. Tapi kalau tulang punggung itu dipikul rakyat kecil sendirian, jangan salahkan kalau ia pun jadi bongkok. Yang kuat justru lari ke surga bebas pajak, menyelundup lewat celah regulasi.
Rakyat kecil tak punya pilihan selain menjual Kebun warisan demi melunasi SPPT. Pada titik itu, pajak bukan lagi instrumen keadilan, melainkan mesin pemindah kepemilikan dari rakyat ke konglomerat atau pejabat korup.
Seorang pejabat pajak pernah bilang, ada mekanisme pengurangan, keringanan, bahkan pembebasan PBB bagi warga miskin. Kedengarannya mulia. Tapi mari jujur: siapa yang punya akses informasi, keberanian birokrasi, dan energi untuk mengurus berlembar-lembar formulir, surat keterangan miskin, tanda tangan lurah, rekomendasi camat, hingga akhirnya sampai ke meja kepala dinas? Bagi rakyat kecil, proses itu ibarat mendaki Gamalama tanpa bekal, hanya untuk menegaskan: “Saya benar-benar miskin.”
Ironis. Negara tahu rakyat itu miskin, tapi masih meminta mereka membuktikannya. Seperti dokter yang meminta pasien batuk berdarah untuk membawa surat keterangan sakit dari RT.
Lalu, apa arti keadilan pajak?
Bukan sekadar angka sama rata, melainkan perlakuan yang selaras dengan kondisi nyata. Yang kaya membayar lebih, yang miskin dilindungi. Yang tanahnya strategis tapi tidak produktif, diberi tarif ringan. Yang punya rumah mewah di kawasan elit, jangan sampai bayar setara dengan petani di kampung.
Keadilan pajak berarti pajak tidak menjadi alat pengusiran terselubung, melainkan jembatan solidaritas. Pajak seharusnya tidak menakutkan, melainkan membanggakan. Kalau sekarang yang terdengar hanya keluhan, maka ada yang salah dengan cara negara menyanyi.
Mari kita ulang kalimat klasik: “pajak adalah kontrak sosial”. Tapi kontrak macam apa yang menjerat leher satu pihak dan membebaskan pihak lain? Kontrak yang adil bukanlah yang memaksa rakyat kecil menjual tanah warisan demi membiayai jalan tol yang justru merugikan mereka. Kontrak yang adil adalah ketika negara benar-benar hadir, bukan hanya sebagai penagih, melainkan juga sebagai pelindung.
Sampai itu terjadi, rakyat kecil akan terus bertanya: pajak ini sesungguhnya untuk siapa? Untuk sekolah anaknya yang atapnya bocor? Untuk sawahnya yang terendam banjir tanpa irigasi? Atau untuk gedung mewah di ibu kota?
Dan di antara tanya itu, mungkin mereka masih bisa tertawa getir. Kata si dalang: “Kalau miskin jangan punya tanah luas, nanti dianggap maling pajak.”
Perilaku kejahatan yang terstruktur ini menjadi satu alaram penting yang perlu sama-sama didiskusikan oleh Rakyat. Jangan sampai nasib yang sama dialami kembali oleh Warga yang lain, sebagaimana 11 Warga Masyarakat Adat Maba Sangadji di Halmahera Timur yang dikriminalisasi karena melawan untuk mempertahankan Tanah Mereka yang diambil Paksa Negara. (*)
**) Ikuti berita terbaru intronusantara di WhatsApp klik link ini dan jangan lupa di follow.