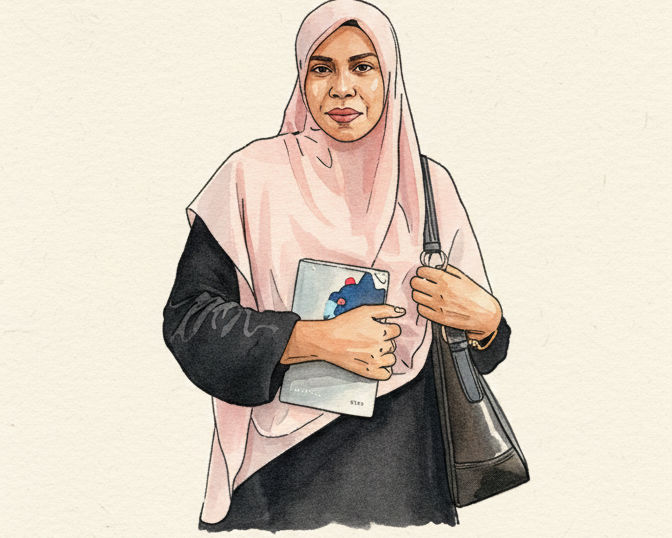Intronusantara — Jumat Malam yang sunyi, nyanyian – nyanyian kenalpot kendaraan mulai terdengar hilang satu persatu. Pada saat yang sama si pemuda bertubuh lemah itu terbaring lesu diatas sofa yang dekil dan busuk.
Bermodalkan satu gelon air minum dirinya menyelami malam bersama buku-buku yang baru dibeli dari tokoh sebelah. Kemudian dilanjutkan dengan menonton Tayangan diskusi dengan Tema ” Oligarki Kian Brutal Sejak Jaman SBY di Perparah Era Jokowi dan IJazah Palsu Presiden yang dipandu Ayman dalam Acara Rakyat Bersuara.
Mark Twain, filsuf setengah komedian, pernah mengguratkan kalimat yang kini terbukti lebih sakti dari ramalan dukun keliling: “Lebih mudah menipu orang, daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah ditipu.”
Dan seperti biasa, manusia modern—dengan gadget canggih dan IQ kolektif yang katanya makin maju—kembali membuktikan bahwa Twain bukan hanya benar, tapi terlalu benar.
Mari kita bicara tentang satu babak klasik dalam sejarah: ketika satu sosok—katakanlah, “Pemimpin Besar Alumni Yang Misterius”—muncul dari rakyat, menyuarakan kesederhanaan, lalu meniti tangga kekuasaan sambil membawa aura merakyat dan narasi haru-biru. Tapi di balik senyumnya yang seolah tulus itu, terselip rahasia: ijazahnya fiktif. Seperti sinetron, tapi sayangnya ini dokumenter.
Namun, yang lebih mencengangkan bukanlah akrobat kebohongannya, melainkan betapa masyarakat tersihir dan membelanya mati-matian—meski bukti sudah dilempar ke muka seperti sandal jepit.
Kebodohan yang Menyamar sebagai Loyalitas, Fanatisme publik terhadap Sang Alumni Misterius begitu dalam, sampai mereka lebih rela percaya bahwa bumi sedang diuji Tuhan, daripada menerima kenyataan bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah. Mereka tidak sedang mencari kebenaran; mereka sedang mencari alasan agar tetap bisa memeluk kebohongan dengan nyaman.
Kita menyaksikan generasi yang bukan tidak bisa berpikir, tapi tidak mau berpikir. Sebab berpikir menyakitkan. Menyadari bahwa idola politik mereka ternyata hanya narasi marketing tanpa substansi, itu seperti menyadari bahwa cinta pertamamu menikah dengan rentenir. Sakitnya dalam, tapi nyata.
Logika Tertindas, Narasi Diagungkan
Di negeri ini, jika engkau membawa dokumen, bukti, analisis forensik, dan saksi hidup, itu semua akan dikalahkan oleh satu hal: caption motivasi di Facebook. Atau lebih tragis lagi, oleh video TikTok dengan backsound lagu sedih dan efek hitam putih.
Pernahkah engkau mencoba menjelaskan soal keaslian dokumen kepada seseorang yang bahkan tak paham perbedaan PDF dan JPG? Mereka akan mengernyit, lalu menjawab, “Ah, itu mah fitnah buzzer oposisi.”
Mereka tidak peduli siapa yang benar. Mereka hanya peduli siapa yang bisa membuat mereka merasa benar.
Sang Pemimpin: Di Mana Ijazahmu, Wahai Yang Merakyat?
Tentu, Sang Pemimpin Alumni Misterius tetap tenang. Ia paham betul hukum pertama politik: semakin besar kebohongan, semakin mudah dipercayai. Ia tidak perlu menjawab. Ia hanya perlu senyum, sesekali menanam pohon, atau menepuk pundak rakyat sambil berbicara dengan logat daerah. Dan rakyat pun luluh. Mereka tak sadar bahwa yang sedang ditanam bukanlah pohon, tapi kebodohan kolektif.
Dan ketika sebagian kecil masyarakat berseru, “Coba tunjukkan dokumen aslimu!”, para loyalis justru menyerang balik: “Kau sakit hati karena tidak punya pemimpin sehebat dia!”—seolah kebenaran bisa dikalahkan oleh rating popularitas.
Berhenti Mendidik, Mulailah Bertahan
Bagi mereka yang masih waras dan mencoba menjelaskan, harap bersabar. Kalian sedang berbicara dengan orang yang sudah mengontrak hatinya ke kebohongan. Berdebat dengan mereka ibarat mencoba menyetrika baju di tengah hujan. Keringnya sebentar, basahnya abadi.
Jadi, mungkin Twain benar—atau bahkan terlalu lembut. Karena hari ini, bukan hanya sulit meyakinkan orang bahwa mereka tertipu, tapi juga berisiko: kau bisa dilaporkan, dibungkam, atau diblokir hanya karena membawa fakta.
Bangsa yang Lupa Bertanya
Yang paling tragis bukanlah adanya pemimpin pembohong. Itu biasa. Setiap zaman punya daftarnya. Yang tragis adalah rakyat yang tidak mau tahu, tidak mau bertanya, dan justru memusuhi orang-orang yang berusaha membuka tirai kebohongan.
Mereka bukan tidak tahu cara membaca. Mereka hanya malas membaca sesuatu yang bisa membuat mereka malu. Karena mengakui bahwa telah ditipu selama bertahun-tahun oleh seorang “pahlawan palsu” berarti harus merombak ulang seluruh keyakinan politik, emosi, bahkan identitas.
Negeri yang Terlalu Pemaaf
Hari ini, kebenaran tidak dibunuh dengan peluru, tapi dengan tepuk tangan. Kebohongan tidak lagi perlu bersembunyi, karena ia disambut dengan karpet merah dan stiker bertuliskan “ikon bangsa”.
Maka ketika kita bertanya, “Mengapa ijazah itu tak kunjung ditunjukkan?”—jawabannya sederhana: karena masyarakat tidak pernah serius memintanya. Mereka terlalu sibuk mengidolakan, sampai lupa menagih akuntabilitas.
Bangsa ini bukan kurang pintar, hanya terlalu baik. Terlalu mudah percaya. Terlalu malas curiga. Dan seperti kata Twain, lebih mudah menipu orang, daripada meyakinkan mereka bahwa mereka sudah menjadi korban—dari narasi, dari figur, dari mitos politik yang dibungkus dengan baju rakyat dan ijazah yang entah dari mana datangnya.
Ditulis Oleh: Surya Rauf